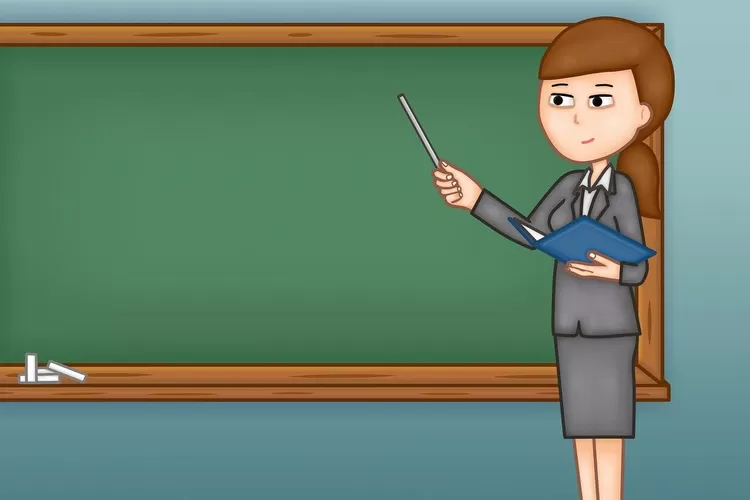OLEH Dr. H. FADLULLAH, S.Ag., M.Si.
Dekan FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Guru selalu berada di jantung perjalanan bangsa. Ia bukan hanya pengajar, melainkan penuntun arah peradaban.
Namun, sejarah pendidikan guru di Indonesia menunjukkan bahwa guru juga sering ditempatkan dalam pusaran kepentingan politik dan ideologi.
Dari masa kolonial hingga kini, pendidikan guru adalah cermin pergulatan bangsa: antara kendali kekuasaan dan hasrat merdeka, antara formalitas gelar dan kompetensi nyata.
Sejarah itu bermula pada 1852, ketika pemerintah kolonial Belanda mendirikan Kweekschool di Surakarta. Inilah sekolah guru pertama di Hindia Belanda yang menggunakan bahasa Belanda sebagai pengantar.
Tujuannya jelas: mencetak tenaga pengajar bumiputera yang loyal kepada pemerintah kolonial. Kurikulumnya praktis, lebih menekankan keterampilan dasar dan disiplin daripada kemerdekaan berpikir. Guru dibentuk bukan untuk membebaskan, melainkan untuk menjaga keteraturan kolonial.
Namun, rakyat tidak tinggal diam. Lahir berbagai sekolah guru yang berhaluan kebangsaan dan keislaman.
Muhammadiyah mendirikan Mu’allimin di Yogyakarta pada 1918, melatih guru sekaligus muballigh yang siap terjun ke masyarakat.
Di Padang Panjang, Rahmah El Yunusiyyah merintis Diniyah Puteri (1923), pusat kaderisasi guru perempuan muslim yang memberi ruang bagi lahirnya kesadaran pendidikan perempuan.
Di Gontor, berdiri Kulliyatul Mu’allimin al-Islamiyah (1936), pesantren modern yang memadukan kedalaman ilmu agama dengan disiplin dan penguasaan bahasa asing.
Sementara itu, Ki Hadjar Dewantara mendirikan Taman Siswa (1922) yang juga memiliki Taman Guru, menanamkan spirit nasionalisme dan kemandirian.
Jejak panjang itu berlanjut setelah Indonesia merdeka. Pemerintah mendirikan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) di hampir setiap kabupaten.
Lulusan SPG, dengan masa studi tiga tahun setelah SMP, bisa langsung mengajar di sekolah dasar. Praktis, murah, dan sesuai kebutuhan bangsa yang sedang membangun.
Banyak guru angkatan SPG dikenang karena pengabdiannya yang tulus, meski hanya berbekal pendidikan sederhana.
Namun, perkembangan zaman menuntut perubahan. SPG resmi dihapus pada 1989. Sebagai gantinya, muncul Diploma II PGSD, lalu Diploma IV, hingga akhirnya ditetapkan bahwa kualifikasi minimal guru adalah sarjana (S1).
Tonggak baru hadir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang mensyaratkan guru memiliki ijazah S1 sekaligus sertifikat pendidik.
Sertifikat itu diperoleh melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG), baik prajabatan maupun dalam jabatan.
Di sinilah muncul pertanyaan penting: apakah semakin panjang jenjang pendidikan otomatis melahirkan guru yang lebih kompeten?
Pengalaman menunjukkan, tidak selalu demikian. Guru lulusan SPG yang hanya menempuh pendidikan tiga tahun bisa menjadi teladan, karena kuat dalam praktik dan dekat dengan murid.
Sebaliknya, banyak lulusan S1 bahkan PPG yang masih kesulitan dalam hal inovasi pembelajaran maupun pengelolaan kelas.
Fenomena ini menyingkap apa yang dapat disebut inflasi mutu. Durasi pendidikan kian panjang, gelar kian banyak, biaya kian besar, tetapi kualitas tak selalu meningkat.
Profesionalisasi yang ditempuh melalui formalisasi justru berisiko mengaburkan substansi.
Guru sejati lahir bukan dari banyaknya jenjang yang ditempuh, melainkan dari kekuatan integritas, keterampilan nyata, dan panggilan hati untuk mengabdi.
Refleksi ini penting, terutama ketika kita sedang menghadapi tantangan pendidikan abad ke-21.
Dunia berubah cepat, anak-anak tumbuh dalam pusaran digital, dan sistem pendidikan dituntut adaptif. Guru dituntut kreatif, bukan sekadar administratif.
Jika profesionalisasi guru hanya berhenti pada persyaratan formal, tanpa memperkuat kompetensi nyata, kita akan kehilangan esensi: guru sebagai pendidik yang menuntun, bukan sekadar pekerja bersertifikat.
Perjalanan panjang pendidikan guru, dari Kweekschool kolonial, sekolah guru Islam, Taman Siswa, SPG, hingga PPG, menunjukkan betapa bangsa ini selalu mencari format ideal.
Pencarian itu akan terus berlangsung. Namun, satu hal tak boleh dilupakan: guru bukanlah sekadar produk dari sistem, melainkan jiwa yang hidup di dalam kelas.
Dan jiwa itu hanya bisa dibentuk dengan pembinaan karakter, penguatan keterampilan, dan ekosistem pendidikan yang mendukung.
Profesionalisasi guru memang mutlak diperlukan, tetapi jangan jatuh ke dalam jebakan inflasi mutu.
Guru yang bermartabat bukan hanya yang memiliki gelar akademik dan sertifikat, melainkan yang benar-benar mampu mendidik, meneladani, dan membimbing anak-anak bangsa menuju masa depan.**